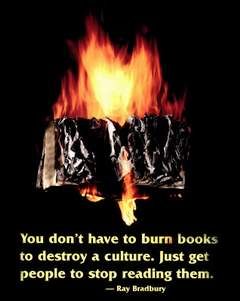Email : humorliner (at) yahoo.com
 Perang blogger. Anda mengenal B.L. Ochman, Warren Kinsella dan Jay Rosen? Dua nama pertama itu berbeda pendapat dengan nama ketiga mengenai ngeblog. Utamanya menyangkut masalah : tulisan di blog itu sebaiknya pendek atau panjang ?
Perang blogger. Anda mengenal B.L. Ochman, Warren Kinsella dan Jay Rosen? Dua nama pertama itu berbeda pendapat dengan nama ketiga mengenai ngeblog. Utamanya menyangkut masalah : tulisan di blog itu sebaiknya pendek atau panjang ?B.L. Ochman, seorang corporate blog strategist dalam artikelnya yang berjudul menarik dan provokatif, How to Write Killer Blog Posts and More Compelling Comments menyarankan agar tulisan di blog itu pendek-pendek saja. Setiap posting sekitar 250 kata, paragrafnya pendek, dan jangan matikan selera humor Anda.
Sementara itu Jay Rosen, profesor jurnalistik Universitas New York dan pengelola blog PressThink.org berpendapat sebaliknya. Ketika tampil dalam konferensi Exploring the Fusion Power of Public and Participatory Journalism (2004), seperti dilaporkan Leonard Witt, pelopor gerakan representative journalism dengan judul Blogging Advice from Jay Rosen: Be Complex ia berpendapat, bahwa gaya ngeblognya komplek, panjang, dalam dan kaya nuansa.
David Akin, moderator konferensi itu, sebelumnya memberikan info menarik : gaya blog Jay Rosen yang panjang itu dikatakan menular. Karena para pembacanya kemudian menulis komentar yang juga panjang-panjang.
“Kunjungi blog dia dan dalam waktu satu setengah jam kemudian Anda masih saja terus membaca, dan berpikir, sehingga tidak salah bila Jay Rosen memberi nama blognya sebagai PressThink,” lanjut David Akin. Bahkan Jay Rosen berpendapat, ia menganggap para pembaca blognya menginginkan sesuatu yang dapat mengebor batok kepala mereka.
Saya, salah satunya. Isi kepala ini yang dibor oleh pemikiran-pemikiran Rosen mengenai kedahsyatan media-media baru, utamanya blog, sungguh mencerahkan. Memabukkan. Dalam artikel yang dimuat di situs organisasi Wartawan Tanpa Tapal Batas berjudul Now I can write what I think ia katakan bahwa anjuran menulis blog itu harus pendek-pendek karena orang tidak punya waktu, sebagai tidak beralasan.
“Saya tidak mempercayainya,” tegasnya. “Alasan dan nasehat itu semata-mata menghambat kebebasan saya untuk menulis segala apa yang saya pikirkan. Karena ide dasar meluncurkan blog PressThink saya adalah pembebasan. Wow, sekarang saya memiliki majalah saya sendiri. Saya mampu menulis segala apa saja yang saya fikirkan !,” seru Jay Rosen.
Tipikal postingan blog dia adalah esai yang panjangnya antara 1.500 sampai 2.500 kata. Kalau B.L. Ochman punya nasehat bagi para blogger agar dalam setiap posting menyertakan banyak sekali tautan, link like crazy, formula itu juga berlaku bagi Jay Rosen. Terdapat sekitar 20-30 hyperlink dalam tiap esainya.
Main sekop di kuburan. Obrolan tentang gaya ngeblog di atas menggoda saya untuk mengungkapnya kembali. Gara-garanya, saya terpicu saat membalik-balik buku berjudul Senandung Cinta dari Rumah Kayu : Catatan Inspiratif Tentang Keluarga, Persahabatan dan Cinta (Daun Ilalang, 2009). Penulisnya adalah Dee, seorang blogger dan Kuti, wartawan yang merangkap sebagai blogger.
Isi buku setebal 229 halaman ini pernah dimuat sebagai tulisan dalam blog rumahkayu.blogdetik.com. Karena sebagian isi buku tersebut mengacu kepada sumber dari blog lain, saya bayangkan formula link like crazy itu juga sudah diterapkan di blog itu pula. Sehingga buku ini mampu berfungsi bolak-balik secara optimal.
Pertama : mampu mem-bumi-kan, alias meng-kertas-kan isi blog mereka yang dari dunia digital. Kedua, juga berfungsi sebagai pintu gerbang bagi mereka yang membaca buku, tetapi belum mengenal blog bersangkutan, untuk kemudian tergoda melakukan petualangan di medan digital, di blog. Untuk membangun interaksi lebih lanjut dengan penulisnya.
Merujuk nasehat David Weinberger dan kawan-kawan bahwa pemasaran adalah percakapan, maka penerbitan isi apa pun sebenarnya bukan terminal akhir suatu perjalanan informasi bersangkutan. Tetapi justru suatu awal. Awal suatu percakapan, dialog.
Tetapi nampaknya, kesan saya, pemahaman konteks untuk membangun sinergi antara media atom yang berbasis kertas dengan media digital yang berbasis bit itu, belum muncul secara kuat dari penerbitan buku ini. Yang terjadi baru semata-mata, dugaan awal saya, adalah niatan polos : pengin punya buku. Salut untuk Dee dan Kuti untuk keberhasilannya untuk yang satu ini.
Tetapi keberhasilannya itu, saya kuatirkan, tidak mampu berlari lebih jauh. Jangan kecil hati, karena implementasi strategi serupa juga sering dilakukan media massa utama, mainstream media, ketika mereka berurusan dengan media digital. Pendekatan dengan trik shovelware ini mereka nilai sebagai hal nalar di mata kaum pengelola media berbasis atom, media kertas. Yaitu ketika isi yang semula terpajang di media cetak “disekop” kembali dari liang kuburnya itu untuk dipajang di media digitalnya.
Walau memang Dee dan Kuti melakukan hal yang sebaliknya. Mula-mula ia memajangnya di media digital, lalu ia pindah ke media kertas, tetapi trik shovelware itu tidak serta merta langsung menjadikan sajian karya bersangkutan selalu tampil serasi dalam media apa pun. Karena media-media itu memiliki karakter masing-masing yang tidak sama. Bahkan bertolak belakang.
Nabi media Marshall McLuhan punya adagium medium is the message, alias menyatakan bahwa bukan isi yang terpenting sebagai pesan, sehingga isi-isi tersebut mula-mula harus dieksekusi sesuai dengan karakter media yang memuatnya. Intinya, menulislah sebebas-bebasnya di blog.
Tetapi bila isi blog itu hendak dijadikan sebagai buku, pelajarilah seluk-beluk dunia penerbitan buku dari A sampai Z dulu. Saya yakin, Dee dan Kuti akan memperhatikan hal ini di masa datang. Tetapi, hemat saya, pelajari seluk-beluk dalam menulis blog dulu. Ini merupakan nasehat, meniru khatib dalam berkhotbah, utamanya dan pertama kali memang ditujukan untuk diri sendiri.
Jerangkong yang menari. Anda pernah menonton acara pamer cakapnya Oprah Winfrey ? Setiap tamunya yang hadir senantiasa membawa jerangkongnya sendiri. Mereka rela dan berani mengeluarkannya dari dalam peti atau almarinya pribadi, kemudian mereka ajak jerangkongnya itu untuk menari atau berdansa di muka dunia.
Tawa yang hadir dari sana, atau linangan air mata kita, semata membuat diri kita merasa sebagai manusia. Bukan sebagai robot atau useful idiot yang patuh terhadap komando untuk tertawa-tawa riuh, tetapi kosong dan hampa seperti dalam acara komedi atau talkshow dengan host orang-orang yang sok lucu di pelbagai televisi kita.
Metafora tentang jerangkong itu saya peroleh dari Susan Shaughnessy dalam Walking on Alligators : A Book of Meditations for Writers (1993). Edisi bahasa Indonesianya berjudul Berani Berekspresi : Buku Meditasi Untuk Para Penulis ( 2004).
Ia mengutip ucapan ucapan Carolyn MacKenzie yang berkata, bila Anda sebagai penulis dan kalau Anda punya jerangkong di dalam lemari Anda, keluarkanlah. Dan menarilah bersamanya. Jerangkong tersebut adalah hal yang paling Anda hindari untuk dituliskan atau diceritakan, seperti rasa malu yang membuat Anda bergidik dan menciut.
Tetapi pada akhirnya hal itu akan muncul juga dalam tulisan Anda. Mengapa ? Karena di sanalah energi jiwa Anda tertimbun. Dengan menuliskannya, Anda meratakannya. Energi itu akan mengalir dalam tulisan dan membuatnya hidup.
Louise L Hay, pengarang dan motivator, sekadar contoh. Dalam buklet Heal Your Body: The Mental Causes for Physical Illness and the Metaphysical Way to Overcome Them (1984), ia menceritakan saat terkena kanker vagina.
Sebagai anak yang pernah diperkosa saat berumur 5 tahun dan sebagai battered child, ia merasa tak aneh bila penyakit yang muncul menyerang vaginanya. Dalam statusnya sebagai guru pengobatan alternatif, ia akhirnya memutuskan untuk berjuang berlandaskan keyakinan metafisika untuk memperoleh kesembuhan. Ia berhasil.
Sosok lain yang menari bersama jerangkong adalah blogger dan content maven, Meryl K. Evans. Dalam tulisannya It’s a Big, Blog World Out There Five Quick Tips to Building a Better Blog (2006), ia mengisahkan salah satu blognya yang lahir ketika ia mengandung anak ketiganya. Blognya berfokus pada masalah kehamilan, tetapi lalu terhenti ketika anaknya lahir karena ia tidak berminat untuk menulis blog seputar topik pengasuhan anak.
Blognya yang lain hadir di dunia ketika ia mempersiapkan diri menerima pencangkokan cochlear implant, untuk merestorasi telinganya yang tuli. Blog tersebut disebut Bionic Ear Blog. Isi blognya yang satu ini meliput tentang proses cochlear implant dan bagaimana menjalani kehidupan bersama alat tersebut.
Dalam perkembangan selanjutnya blog ini diperkaya dengan tulisan tentang kehidupan Meryl K. Evans sebagai penyandang tuli dan pengalamannya menemukan hal-hal baru sebagai orang tuli pada sepanjang 30 tahun menjalani kehidupan.
 Orang asing. Di dalam Rumah Kayu-nya Dee dan Kuti nampaknya tarian jerangkong itu tidak pernah terlihat jelas berkelebat di dalamnya.
Orang asing. Di dalam Rumah Kayu-nya Dee dan Kuti nampaknya tarian jerangkong itu tidak pernah terlihat jelas berkelebat di dalamnya. Barangkali karena semua tokoh yang hadir dalam buku itu hanya nampak sebagai sosok-sosok bayangan di balik kabut, walau dari sana terdengar cinta dan cinta itu disenandungkan oleh mereka. Sementara jerangkongnya sudah digedong, dibungkus rapat seperti mumi, dan disimpan dalam kotak besi yang tersembunyi.
Dalam dialektika dunia komedi, Dee dan Kuti rupanya lebih memilih sebagai orang-orang normal belaka Artinya, selera humor orang-orang normal semacam ini diwujudkan dengan cara menghafalkan lelucon milik orang lain dan lalu menceritakannya kepada orang lain.
Bukan suatu kebetulan, sekadar ilustrasi, bila ia tiba-tiba tergoda menceritakan lelucon mengenai jenis kelamin komputer pada bagian awal bukunya itu. Padahal itu lelucon milik orang lain dan bukan bersumber dari wisdom kehidupan yang mereka jalani.
Padahal menurut saya, Dee dan Kuti harus menjadi komedian yang sejati. Yang orisinal. Yang harus mentransformasikan seluruh hidupnya menjadi komedi itu sendiri. Salah satu caranya : membangunkan jerangkong-jerangkongnya sendiri yang selama ini tersimpan rapat di lemari, dan lalu menarikannya di muka dunia.
Sayang, jerangkong itu sulit saya temukan di buku Rumah Kayu itu. Baru ketika mengakses blognya, saya terantuk pada posting berbunyi : “Pada buku pertama ini (oh ya, kami memang berencana menerbitkan buku rumahkayu dalam beberapa seri) kami juga menulis soal si kecil, bagaimana sampai dia bisa menjadi anak Dee dan Kuti (yang belum setahun menikah namun sudah punya anak berusia sekitar enam tahun).”
Pikir saya, mengapa Dee dan Kuti tidak memfokuskan isi blog dan atau bukunya itu pada topik tentang adopsi anak saja ? Bukankah blognya berpeluang menjadi lebih berhasil bila menggarap suatu ceruk, niche, yang benar-benar khusus dan spesifik ?
Bukankah topik adopsi anak itu dapat direntang perbincangannya dari masalah ginekologi, psikologi, bahkan sampai cerita tentang sosok tukang adopsi anak kelas dunia semacam Madonna hingga (foto) Angelina Jolie ?
 Guru yang kejam. Sebagai pengelola blog kajian tentang print on demand, yang memajang manifesto bahwa setiap orang berhak menerbitkan bukunya sendiri, maka penerbitan buku Rumah Kayu itu pantas memperoleh acungan jempol.
Guru yang kejam. Sebagai pengelola blog kajian tentang print on demand, yang memajang manifesto bahwa setiap orang berhak menerbitkan bukunya sendiri, maka penerbitan buku Rumah Kayu itu pantas memperoleh acungan jempol. Keberanian Dee dan Kuti untuk menerbitkan isi blognya menjadi buku, jelas menjadi inspirasi bagi para blogger lainnya.
Pengalaman ini, di hari-hari mendatang, akan sangat berharga sebagai batu pijak mereka berdua dalam melangkah. Apalagi pengalaman dikenal sebagai guru yang paling kejam, ia memberi dulu kita ujian dan sesudahnya baru memberi kita pelajaran.
Ada satu hal yang menggelitik saya.
Apakah pengelolaan blog sampai penerbitan isinya menjadi sebuah buku itu sudah masuk dalam strategi besar bagi Dee dan Kuti ke depan ? Karena terdapat sebagian orang yang berkeyakinan bahwa dengan menulis atau menerbitkan buku dengan mengira bahwa di luar sana terdapat pasar yang menantikannya. Pendapat itu jelas keliru.
Penerbitan buku tidak sesederhana, dengan pendekatan navel gazing semacam itu. Apalagi ketika setiap orang mampu mengelola blog, juga menerbitkan buku, persaingan menjadi riuh, seringkali membuat nilai ekonomi tidak melulu atau tidak lagi berada dalam ranah keduanya.
Tren yang ada di depan ini, buku-buku itu cenderung digunakan tak ubahnya sebagai bentuk canggih dari kartu nama. Diberikan secara gratis, guna mendongkrak reputasi penulisnya.
Informasi dalam blog dan buku disebarkan secara gratisan, free dengan tujuan membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap penulisnya guna meraih nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Alias freemium (terima kasih Chris Anderson atas istilah ini dalam bukunya berjudul Free), misalnya dengan tampil sebagai nara sumber media, konsultan dan pembicara.
Sebagai blogger, hal itu pula yang beberapa kali terjadi pada diri saya. Termasuk memperoleh hal yang surprise, yaitu ketika memperoleh kiriman buku dari Dee dan Kuti ini yang secara pribadi belum saya kenal, dan kemudian dipercaya untuk memberikan pendapat tentang buku tersebut.
Sebagai bacaan, kalau saja kita sudah mempercayai penulisnya sebagai orang yang kompeten untuk subjek yang ditulisnya, buku ini cukup menghibur. Tetapi saya agak terganggu membaca di halaman sampul belakang yang berbunyi, “sebuah buku yang berisi pesan-pesan cinta, persahabatan dan kehangatan sebuah keluarga.”
Saya pengin, kata “pesan-pesan” itu diganti menjadi “cerita-cerita.” Kata pesan berkonotasi menggurui, berada di atas, tetapi kata cerita nampak lebih egaliter.
Merujuk hal itu, seperti bunyi judul tulisan ini, saya merasa terantuk di “Pintu” alias pada bab pertama buku Rumah Kayu ini. Saya kejedot. Karena tulisan pertama, “Ada Apa Dengan Cinta ?,” yang menurut saya seharusnya ditulis sebagai cerita dan bukan paparan diskursif yang mirip materi diskusi yang kering itu.
Pada lembar sebelumnya saya berharap memperoleh data nama sebenarnya dari Dee dan Kuti, agar mudah ditemukan oleh mesin pencari. Saya tidak puas dengan biodata yang nampak justru banyak “menyembunyikan” dirinya di buku itu. Meminjam teknik penulisan buku drama, pada halaman awal sebaiknya dicantumkan data para pelaku cerita. Siapa Kuti, siapa Dee, Pradipta, sampai kakak berambut poni.
Kembali ke pemilihan judul artikel pertama itu, “Ada Apa Dengan Cinta ?” itu. Sayang, dalam isinya hanya merujuk keterangan singkat mengenai film yang berjudul sama itu sebatas sebagai tempelan. Saya mengharap sebetulnya, ada cerita bagaimana cinta dalam filmnya Dian Sastro (“saya merekam ucapan almarhum ayah Dian saat ia diwisuda 1985 sebagai sarjana sastra UI”-BH) itu hadir dan menari. Lalu misalnya merujuk cinta yang terjadi dalam film lain, Love Story misalnya, kemudian diramu sebagai jalinan cerita untuk mengupas topik pembuka itu.
Usulan saya : dengan menyebutkan pada tulisannya, misalnya judul, alur cerita, nama tokoh, penggambaran karaker sampai ucapan yang memorable dari sesuatu tokoh dalam novel terkenal atau film, Dee dan Kuti seolah mampu merengkuh pembacanya untuk hadir bersama tokoh-tokoh yang sama-sama kita kenal sebelumnya.
Tontonlah film Sleepless in Seattle (1993). Ada adegan mengharukan saat para pria bareng-bareng menangis ketika mengenang adegan dramatis dalam film perang The Dirty Dozen. Atau dalam film seri (kawak) Remington Steele, di mana aktornya Pierce Brosnan, selalu saja mengaitkan adegan yang ia alami sambil menyebut judul-judul film yang relevan.
Dee dan Kuti memang telah berusaha merangkul kita. Tetapi dengan Sun Tzu. John Gray. Sampai Viskram Seth. Terima kasih untuk ikhtiarnya itu.
Akhirnya, meminjam bahasa Jepang, untuk buku perdananya itu saya hanya bisa bilang tentang tulisan saya ini kepada Dee dan Kuti :
Isoku mung iki.
Mugi murakabi.
Wonogiri, 6-17/11/2009