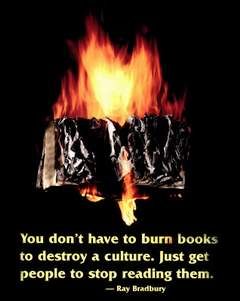Email : humorliner (at) yahoo.com
 Swiss.
Swiss.Negeri yang bersih.
Kritikus dan novelis Perancis André Gide (1869–1951) melukiskan betapa di sana “Anda tak akan berani membuang puntung rokok ke danaunya dan sama sekali tak ada corat-coret grafiti di WC umumnya.”
Tetapi Swiss juga tak luput menjadi bulan-bulanan. Dalam film The Third Man (1949) seorang Orson Welles (1915–1985) telah menambahkan ejekan itu dalam skenario karya penulis Inggris, Graham Greene (1904–1991) :
“Di Itali, ketika rejim Borgia berkuasa selama tiga puluh tahun berlangsung teroe, perang, pembunuhan dan banjir darah, tetapi juga menghasilkan Michelangelo, Leonardo da Vinci dan the Renaissans.
Di Swiss, mereka tenteram membina persaudaraan, demokrasinya berjalan sepanjang lima ratus tahun secara damai, tetapi apa yang bisa mereka hasilkan ? Jam ku-kuk !”
Dan kini, juga menghasilkan seorang Roger Federer.
“Very Swiss !”
Demikian tandas Vijay Amritaj, komentator tenis yang terkenal di televisi Star Sports. Ia berkomentar ketika penyandang 15 gelar Grand Slam itu dalam proses menekuk Lleyton Hewitt, “kangguru” terakhir yang mampu bertarung di Melbourne Park.
Vijay benar. Roger Federer adalah presisi. Seperti jam Swiss dibuat. Di lapangan setiap bola yang ia tembakkan dengan raket Wilson KFactor KSix-One Tour 90 (kini ganti dengan raket Wilson BLX SixOneTour-90. Info ini dikirimkan sobat Pedhet Wijaya langsung dari Melbourne. Thanks, buddy !) itu ibarat perjalanan detik-detik jarum jam yang berputar.
Dengan konsistensi.
Dengan ketepatan.
“Di masa-masa awal karir saya, problem utama saya adalah konsistensi.” Demikian tutur petenis kelahiran Basel 8 Agustus 1981 itu. Akibat dari sifat umum sebagai anak muda, yang temperamental. Tetapi kini, lanjut Federer : “Saya belajar untuk bisa lebih sabar.”
Terkait kesabaran itu wartawan Paul Weaver dari koran The Guardian merujuk bahwa ketahanan mental Roger Federer merupakan hasil dari latihan, produk rekayasa. Sementara Nadal lebih alamiah. Tetapi kita menjadi saksi bagaimana jam Swiss itu berdetak secara menakjubkan. Santun tetapi kejam dalam menelan satu demi satu, semua musuh-musuhnya.
Perjalanan karier tenis Roger Federer mungkin sudah tertakdir sebagai perjuangan untuk meraih kesempurnaan. The Roger Federer Story : Quest for Perfection. Itulah judul buku yang ditulis Rene Stauffer, konon salah satu jurnalis ternama tenis dunia, yang terbit pada tahun 2007.
Kesempurnaan itu pula yang barangkali membuatnya pantas didaulat sebagai atlet papan atas dunia yang terpilih sebagai salah satu dari 100 Orang Berpengaruh Di Dunia oleh Majalah TIME edisi 14 Mei 2007 (“ini hadiah Niz dari London.”). Fisiknya yang bugar membuatnya tidak pernah mengundurkan diri ketika terjun dalam pertandingan utama. Tidak seperti nasib malang seteru “abadinya”, juga petenis hebat asal Mallorca, Spanyol : Rafael Nadal.
Pride and ego. “Saya sangat menyesal,” demikian kata penghiburan dari Andy Murray saat menyalami Nadal yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Dalam pertandingan merebut kursi semi final Australia Terbuka 2010 itu, posisi angka Nadal telah tertinggal, 3-6, 6-7 (2-7) dan 0-3. Ketika cedera lututnya yang kronis sudah tak tertahankan lagi, ia pun melemparkan handuk.
Dunia tenis kuatir berat. Seorang Kevin Mitchell, juga wartawan dari surat kabar The Guardian menulis, cedera tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang karir gilang-gemilang Rafael Nadal di masa-masa mendatang.
Cedera lutut yang sama membuat Nadal absen mempertahankan gelarnya di Wimbledon tahun lalu. Di final, petenis Amerika Serikat yang paling sering ketemu, Andy Roddick, gagal mengadang Roger Federer dalam meraih trofi Grand Slam ke-15. Akibatnya Federer melebihi prestasi si tukang servis geledek dari AS, Pete Sampras.
“Lutut,” kata Louise L. Hay dalam bukunya Heal Your Body : The Mental Cause For Physical Illness and The Metaphysical Way to Overcome Them (1985), “mewakili harga diri dan ego.”
Sementara itu, masalah terkait lutut, menurutnya, dipicu oleh “kebandelan ego dan rasa harga diri itu. Tidak mampu bersikap lentur. Dicekam rasa takut. Tidak fleksibel. Pantang menyerah.”
Dari paparan Louise L. Hay (“kajian yang masuk disiplin ilmu baru, the biology of believe ini, yang kepingin saya buatkan blog tersendiri tetapi belum kesampaian itu “) kita bisa menebak memang begitulah psyche seorang Rafael Nadal selama ini.
Ia seorang matador petarung, brave fighter, yang enerjinya tak pernah habis terkuras. Cedera kronis lututnya itu menjadi logis akibat dari rasa gerah dan geram karena terlalu lama menjadi bayang-bayang dari Federer. Selalu saja dirinya menjadi nomor dua. Sempat ia duduk di peringkat satu dunia. Tetapi Federer dengan konsisten, kemudian mampu menggusurnya lagi.
Lihatlah data pertarungan keduanya yang benar-benar sengit.
Keduanya sama-sama memenangkan Grand Slam pada tiga lapangan yang berbeda secara berurutan. Rafael Nadal menjadi raja di Perancis Terbuka 2008, Wimbledon 2008 dan Australia Terbuka 2009. Sementara Roger Federer tampil megah di Amerika Serikat Terbuka 2008, Perancis Terbuka 2009 dan Wimbledon 2009.
Meminjam kasus pemasaran klasik dari bukunya Al Ries dan Jack Trout, Positioning : The Battle For Your Mind (1986), perjuangan Nadal itu kiranya dapat diwakili oleh upaya perusahaan persewaan mobil di Amerika, Avis. Perusahaan itu juga merasa posisinya terpatok melulu di kursi nomor dua. Sementara posisi nomor satu ditenggeri oleh Hertz.
Kampanye iklan perjuangan Avis itu kemudian tercatat sebagai contoh klasik dalam sejarah pemasaran : bagaimana Avis menempatkan diri dalam posisi kuat untuk bertarung melawan sang jawara. Lihatlah tagline iklannya :
“Avis hanya nomor dua dalam bisnis persewaan mobil, tetapi mengapa Anda harus bersama kami ? Karena kami berusaha keras lebih baik dalam melayani.”
Dalam kasus Nadal, semboyan we try harder-nya Avis itu kiranya membuat lututnya berderak dan berteriak. Ia gagal menuju semi final. Nadal pun terpental.
Kini siapa kampiun di Rod Laver Arena 2010 ini ?
Apakah Andy Murray yang akan memenangkan juara Australia Terbuka ? Jangan lupa, ia punya senjata sekaliber peluncur roket untuk servis pertamanya. Ia telah mengalahkan Federer empat kali, Nadal dua kali, dan peringkat keempat Novak Djokovic sebanyak tiga kali.
Bila anak muda usia 22 tahun itu juara, ia merupakan orang Inggris pertama tampil dengan mahkota Grand Slam sejak Fred Perry menjuarai kandangnya sendiri, Wimbledon, di tahun 1936.
Itu waktu yang sudah lama sekali. Sama dengan mimpi tim sepakbola Indonesia untuk bisa masuk final Piala Dunia. Apalagi ketika terjun di Paris 1938, negara kita masih sebagai negara jajahan Belanda !
Siapakah jago Anda di hari Minggu mendatang ?
Siapa jago teman saya Pedhet Wijaya yang kini sedang pula ada di Melbourne ?
Wonogiri, 27 Januari 2010.
P.S. : Ditulis dengan menguping nomornya Mozart, Simfoni No. 40, di hari ulang tahunnya yang ke 254.
Kebetulan tanggal tersebut 5 tahun lalu di Pesta MURI Semarang (2005) saya mendeklarasikan komunitas penulis surat pembaca se-Indonesia, Epistoholik Indonesia (EI). Juga menyatakan tanggal 27 Januari sebagai Hari Epistoholik Nasional, dan saat itu saya meraih Rekor MURI yang kedua.
Pesta hebat akan dirayakan, Insya Allah, di surat kabar Koran Tempo, edisi Jumat, 29 Januari 2010. Oleh Mas M. Ravik, wartawannya, kiprah EI akan dibeberkan di sana. Semoga dapat menjadi inspirasi, bahwa dengan menulis itu membuat kita mampu berkontribusi bagi sesama.