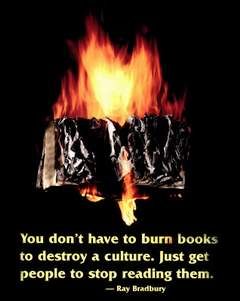Oleh : Bambang Haryanto
Email : humorliner (at) yahoo.com
Cerita lucu dari Marshall McLuhan tidak berlaku di Taman Budaya Surakarta siang itu.
Cerita tersebut bersumber dari buku terkenalnya
Understanding Media : The Extensions of Man (1965).
Buku ini saya beli dari Toko Buku Gramedia Gajah Mada Jakarta, 25 Mei 1977. Via pos dari Mandungan. Hasil honor menulis di koran
Merdeka, Minggu, Februari 1977.
Nabi media asal Kanada ini pernah cerita tentang suku buta huruf asal Afrika ketika ramai-ramai menonton film.
Karena memahami cerita dalam film dibutuhkan keterampilan literasi yang tinggi, film bagi suku Afrika film menjadi tontonan yang membingungkan mereka. Adegan lucu pun terjadi.
Ketika ada tokoh yang kena tonjok dalam sesuatu adegan, lalu menghilang dari layar, muncul kehebohan. Para penonton asal benua hitam itu akan ramai-ramai berlarian ke belakang layar. Mereka ingin mengetahui nasib aktor tersebut.
“Menyaksikan filmnya Charlie Chaplin,
The Tramp, penonton film Afrika menyimpulkan bahwa orang-orang Eropa itu tukang sihir hebat. Karena mereka mampu menghidupkan mahkluk-makhluk yang telah meninggal dunia,” demikian cerita McLuhan.
Film tentang seseorang yang telah meninggal juga ditayangkan di siang teduh, Rabu, 4 Januari 2012, di Taman Budaya Surakarta, Solo. Taman ini kemudian bernama Taman Budaya Jawa Tengah.
Saya ikut menonton adegan yang tersaji. Sayangnya dalam layar yang pucat, karena
lumens proyektornya tidak mampu menyaingi sinar matahari pendopo besar tersebut.
Mandi di Sasonomulyo. Seseorang yang meninggal itu bernama lengkap Drs. Martinus Joseph Murtidjono (61). Nama gelarnya dari Kraton Surakarta : Kanjeng Raden Tumenggung Sudjonopuro. Tahun 1975-1980, di Sanggar Mandungan Muka Kraton Surakarta, saya mengenalnya sebagai Eyang Murti.
“Murti baru belakangan gabung di Mandungan,” tutur Sudarto (76), pegawai Pusat Kebudayaan Jawa Tengah (PKJT) Sasonomulyo era 70-an yang kini masih bekerja di ISI Surakarta. Saat itu pria kurus asal Mangkubumen Solo tersebut, yang memiliki kulit kehitaman yang terkenal dengan ciri syal yang selalu melingkari lehernya, menjelang lulus kuliah di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada.
“Kalau Murti datang dari Yogya,” lanjut Mas Darto, “pasti nginepnya juga di Mandungan. Kalau pagi, bawa
ciduk isi sabun, sikat gigi dan odol, untuk menumpang mandi di Sasonomulyo.” Di Mandungan, yang saya ingat, ia sering membawa mesin tulis. Flute. Memainkan gitar, nomornya Villa Lobos. Naiknya Yamaha bebek hijau.
Ia juga memberi saya bacaan menarik. Himpunan guntingan cerita bersambung dari harian
Kompas yang dilanggan oleh ayahnya, tokoh Tentara Pelajar (TP) yang terkenal di Solo : Mardeyo Jungkung.
Antara lain cerita
thriller, saya lupa judulnya, tentang agen rahasia Perancis yang berusaha membongkar kudeta merangkak yang dilakukan justru oleh presiden Perancis yang ingin menjadi satelit Uni Sovyet di masa perang dingin. Juga cerita berjudul
Salamander yang menegangkan.
Minatnya terhadap
thriller kiranya yang juga membuat Murtidjono tak jarang berbagi cerita dengan saya. Ia suka sinis atau getol melucukan cerita-cerita perjuangan fisik tokoh-tokoh seangkatan ayahnya saat mereka berperang melawan Belanda. Utamanya untuk cerita-cerita yang menurutnya fiktif, rekaan atau yang bombastis.
Ketika mengintip sebagian buku yang ia bawa ke Mandungan, antara lain saya menemui nama Søren Kierkegaard sampai Teilhard de Chardin. Sebagai mahasiswa Fakutas Keguruan Teknik (FKT) Jurusan Mesin UNS, yang terbius ikut berkesenian di Mandungan, saya tidak
ngeh atas nama-nama itu. Bahkan sampai kini.
Tetapi pertarungan intelektual antara kita, yang menarik dan bikin kecanduan sehingga berlangsung hampir tiap malam, adalah saat kami bertanding main
scrabble. Benar-benar malam demi malam Mandungan sering sama-sama kita habiskan.
Kompetitornya bukan main-main. Ada Profesor HB Sutopo (almarhum), Conny Suprapto, Marsudi, Broto Dompu (Ekonomi UGM), juga Narsen Afatara yang kandidat doktor dan dosen Seni Rupa UNS. Saat ketemuan di Taman Budaya Surakarta tadi Cak Narsen mengaku sambil tertawa : “Saya dulu bagian yang
kalahan.”
Saya kena marah. Sekadar kilas balik, satu-satunya
action dia yang rada “nylekit” pada saya adalah saat saya ia pinjami ensiklopedia.Lalu saya baca sambil tiduran. Tentu saja, saat tidur halaman dalam ensiklopedia itu kemudian saya tutupkan ke muka saya.
Saya lalu rada dimarahi olehnya. Karena menurutnya kertas ensiklopedia itu akan terkotori dan rusak oleh keringat jidat saya. Betul juga. Mungkin justru karena teguran itulah, saya dapat hikmah. Pada tahun 1980 kami berpisah. Saya malah melanjutkan kuliah di Jakarta yang mata kuliah intinya tentang teknik dan organisasi bahan pustaka (termasuk buku, juga ensiklopedia), di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fak. Sastra Universitas Indonesia.
Bisa ketemu lagi dengan Eyang Murti, tanggal 9 Desember 1982, di Pemakaman Kajen, Wonogiri.Tidak saya duga, dirinya bersama Anang Syahroni, Putut Handoko Pramono dan Wahyu Sukirno, ikut melayat saat ayah saya Kastanto Hendrowiharso (54) meninggal dunia.
Saat saya tinggal di Jakarta, beberapa kali kami bertukar surat dan kartupos. Ketika dirinya diangkat sebagai Kepala TBS dan saat ayahnya meninggal dunia. Murtidjono pernah pula mampir ke kos saya di Rawamangun, sekitar tahun 1982. Saat itu saya menjual buklet tipis berisi artikel Harold Rosenberg, berjudul "Apa itu seni ?." Murti nampak agak kecewa, karena mungkin ia mengharapkan buku yang tebal. Sementara buklet itu hanya belasan halaman saja.
Di tahun 2007, saat membaca-baca koran
Solopos yang mewartakan bahwa
Pak Topo dan Eyang Murti pensiun, saya telah menulis kenangan di blog saya. Berkat tulisan itu pula saya bisa kontak lagi dengan Murti.
Lewat email, sms dan Facebook, kami pun berhubungan. Juga saat Murti dirawat di Rumah Sakit Brayat Minulyo. Saya baru tahu belakangan ia sakit leukemia. Ini penyakit seniman yang lebih elit, cetus sahabatnya, Efix Mulyadi. Saat itu Murti via sms mengatakan “telah diperbolehkan pulang, jangan kuatir.”
Jalan kebudayaan. Mas Darto, Mas Ardus, Agustinus Sumargo, Basnendar, Budi, Hajar Satoto (diatas kursi roda), Cak Narsen, Prof. Darsono, Anang Syahroni, Gunarni, Harsoyo, Listyawati, Mayor Haristanto, Niken, Prof. Rustopo, Yantono, saya dan ribuan warga komunitas seniman Jawa Tengah dan DIY, siang itu bisa dipersatukan kembali dalam satu situasi yang sama. Sama-sama merasa kehilangan atas wafatnya Murtidjono.
“Saya pribadi harus berterima kasih kepada Mas Murti, karena dirinya telah mempertemukan saya dengan para raksasa seniman hebat yang berkiprah di Solo,” kata Halim HD,
networker kebudayaan yang mengenal almarhum sejak 40-an tahun yang lalu.
“Kami sama-sama kuliah di Filsafat UGM, satu tahun tidak pernah ketemu di kampus. Tetapi ketemuannya di jalan kebudayaan. Termasuk ketika di tahun 1978 Mas Murti mengundang saya ke Solo. Ketika itu Mas Murti sedang membidani embrio Taman Budaya Surakarta,” cetus Halim HD dalam orasi yang sangat emosional.
Sejak itu, dalam hitungan masa 26 tahun, lanjutnya, Murtidjono ia sebut telah berhasil membangun fondasi yang kemudian memunculkan Taman Budaya Surakarta sebagai “rumahnya seniman, rumahnya rakyat, sekaligus rumahnya kebudayaan rakyat.”
 Kontroversial.
Kontroversial. Film yang menggambarkan sebagian fragmen kehidupan Murtidjono itu saya lihat dari arah belakang layar. Seperti saat kita menonton wayang.
Tak ada narasi dalam film itu. Karena narasi yang mendominasi saat itu adalah urutan upacara penyerahan jenazah dari fihak keluarga kepada fihak Taman Budaya Jawa Tengah. Disusul upacara keagamaan secara Katholik. Ucapan belasungkawa dari kalangan seniman, termasuk dari seniman Yogyakarta yang diwakili Landung Simatupang. Pembacaan riwayat hidup Murtidjono hingga doa pemberangkatan.
Di film itu nampak Murti sedang berpidato yang didampingi istrinya, Ningsri Sadiarti. Saya baru tahu saat itu, ia adiknya Bambang Sumantri yang teman kuliah saya di FKT-UNS, Jurusan Mesin.
Pasangan Murti-Ningsri di film itu nampak ceria. Banyak senyum. Sepertinya Murti sedang memuji atau berbagi cerita lucu tentang istrinya kepada audien.
Adegan yang memikat kemudian adalah saat Murti mencium pipi istrinya. Adegan pasangan suami-istri yang dikaruniai putra-putri Gernatatiti (menantu Panji Nugroho), Bramwasdanto dan Oki Nandhi Wardhana sangat mengesankan. Membahagiakan.
Tetapi adegan film berikutnya bagi saya kontroversial. Ada deretan bapak dan ibu, sepertinya semuanya pegawai negeri. Mereka semuanya nampak berpakaian resmi, berlaku takjim dan bahkan dengan
gesture menunduk-nunduk. Mereka berbaris berurutan untuk bersalaman dengan Eyang Murti yang didampingi istrinya.
Mungkin ini acara halal-bihalal. Atau peringatan ulang tahun dirinya. Tetapi Murtijono saat itu tampil tanpa jas. Juga bukan berbaju batik. Melainkan hanya dengan kaos warna hitam. Bahkan tanpa lengan. Seperti foto dalam profil pribadinya di akun Facebook (foto).
“Kontroversial. Itulah kakak saya itu,” demikian awal pidato dari fihak keluarga yang berduka. “Dalam pertemuan keluarga, baik eyang sampai orang tua kami, kalau ada sesuatu yang menurut kakak saya dianggap keliru, ia akan mengritiknya. Tetapi sebenarnya, di balik itu ada keinginan yang baik, untuk menuju sesuatu yang lebih baik.”
Cerita satu ini mengingatkan saya komentar seorang nara sumber dalam acara balap mobil F-1 di televisi ketika mengobrolkan sosok pembalap F-1 dari tim Scuderia-Ferrari, Fernando Alonso.
Komentator itu bilang, “kalau pembalap bagus, sebagian besar orang menyukainya. Tetapi bagi pembalap yang hebat, pasti ada sebagian yang menyukai dan sebagian lain membencinya.” Mungkin itu pula profil sosok seorang sahabat yang bernama Murtidjono.
Adios, amigo. Siang itu, jam 11.13, mobil jenazah PDIP Surakarta yang bagian belakangnya ada fotonya Jokowi-Rudi, berangkat meninggalkan pendopo Taman Budaya Jawa Tengah. Membawa peti jenazah rekan saya yang sesama aktivis di Mandungan, di masa-masa muda dulu.Makam keluarga Njithengan-Kayangan, Karangpandan, Karanganyar, kini menjadi tempat istirahatnya yang abadi.
Film tentang Murtidjono sebagai insan, sebagai seniman, juga tentang hidup kita atau mereka yang pernah bersentuhan dengan dirinya, baik yang suka atau yang benci, semoga akan tetap tertayang di layar kehidupan kita masing-masing.
Demikianlah siang itu akhirnya film tentang sobat saya Murtidjono selesai ditayangkan. Layar pucat itu kembali putih bersih. Ketika sosoknya hilang dari layar, tidak seperti perilaku suku Afrika dalam kisah McLuhan, saya tidak mencari-cari dirinya ke balik layar.
Karena saya sudah ada di sana. Di balik layar. Sambil merangkai kenangan yang berkelebatan di benak tentang dirinya. Saya mengharapkan sobat Murtidjono kini sudah berada di tempat lain, di tempat yang paling enak.
Paling baik dari yang terbaik.
Di sisi Sang Khalik.
Selamat jalan, sahabat.
Sugeng tindak, Eyang Murti.
Wonogiri, 4 Januari 2012