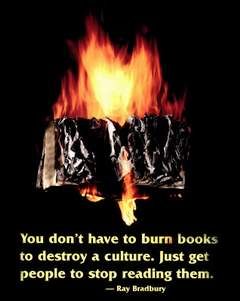Wawancara tertulis Bambang Haryanto oleh Redaktur Indonesia Buku, Diana AV Sasa, 21 Agustus 2009
Catatan : Media digital adalah media limpah ruah. Anasirnya yang terbuat dari sinyal-sinyal elektronik, tidak terbatas keberadaan maupun stoknya untuk mampu dieksploitasi setinggi imajinasi yang dapat dijangkau oleh manusia.
Suatu karunia, saya sebagai seorang epistoholik, mendapat kehormatan untuk menjadi subjek wawancara Redaktur Indonesia Buku, Diana AV Sasa. Hasil akhirnya berupa tulisan berjudul
Bambang Haryanto: Membaca dan Menulis Seperti Donor Darah. Tulisan yang komprehensif.
Sesuai dengan fitrah media digital dan berniat mengunggah limbah atau cipratan-cipratan warna yang tersisa dari tulisan di atas, dalam blog ini saya sajikan jawaban saya secara penuh dalam wawancara melalui email tersebut. Semoga bisa melengkapi lanskap yang telah ada (BH).
Informasi terkait :
Bambang Haryanto: Membaca dan Menulis Seperti Donor DarahInilah 5 Buku Favorit Presiden Epistoholik IndonesiaKaum Epistoholik Punya 5 Blog TongkronganVirus Obama Menyebar di Puncak BrengosSurat dari Presiden Rakyat Epistoholik  Pertanyaan : Sejak kapan senang menulis ? Jawab
Pertanyaan : Sejak kapan senang menulis ? Jawab : Sejak SMP, sekitar tahun 1968. Saya mengirimkan lelucon ke majalah Kartika Chandrakirana, majalahnya ibu saya (Sukarni) sebagai istri TNI-AD.
Lelucon saya dimuat, mendapatkan honor. Rp. 200,00. Bonusnya : tak jarang ibu saya mengungkap kembali lelucon yang saya tulis itu dalam pertemuan keluarga. Saya malu mendengarnya, tapi ya, senang juga.
Sebelum momen itu, menulis surat dan menulis reportase pertandingan sepakbola. Surat itu surat cinta (monyet), berbahasa Indonesia tetapi abjadnya Rusia. Kebetulan ayah saya saat itu dengar-dengar mau dikirim belajar ke Rusia, ia belajar otodidak, dan saya ikut membaca-baca buku pelajarannya.
Sementara yang reportase, sesudah menguping radio tetangga saat siaran pertandingan sepakbola, saya tergerak untuk menuliskannya. Walau untuk dibaca-baca sendiri. Isi majalah Ibu saya itu juga memicu saya untuk menulis cerpen, kisah tentara gerilya dan kekasihnya. Tapi tak selesai. Di SMP Negeri 1 Wonogiri, ketika puisi saya dipajang oleh guru saya di papan majalah dinding, itu momen yang menggetarkan saya.
Biasanya menulis apa ? Macam-macam, sampai saat ini. Waktu SMP dan STM Negeri 2 Yogyakarta, saya menulis lelucon untuk majalah Aktuil dan Varia Nada. Waktu kuliah di IKIP Surakarta (saat itu)/UNS Sebelas Maret, pernah menulis artikel sosial di majalahnya ITB, Scientiae. Pernah menjadi wartawan lepas, menulis tentang musik dan teater di Solo. Juga mengirim berita budaya ke Kompas sampai menulis cerpen ke Sinar Harapan dan majalah Gadis.
Saat ini, saya pernah menulis di kolom Teroka-nya Kompas tiga kali : dua bertopik komedi dan satunya, sepakbola. Topik terakhir ini juga pernah saya tulis di Tabloid BOLA. Topik media sosial di Internet dan terorisme, baru saja muncul di harian Solopos, Solo. Dua buku kumpulan lelucon, terbit tahun 1987. Tentu saja, sejak 1973, terus saja menulis surat-surat pembaca.
Apa fungsi/manfaat menulis buat Anda ? Dengan menulis, kita mengekpresikan gagasan dan jati diri.
Episto ergo sum. Saya menulis (surat pembaca) karena saya ada. Manfaat menulis adalah membuat karunia Allah yang paling demokratis dan ada di antara kedua kuping kita itu berfungsi baik, syukur bila berfungsi sebaik-baiknya.
Menulis juga bermanfaat bagi kesehatan. Dengan menulis, saat kita berderma pengetahuan, justru akumulasi pengetahuan yang ada pada diri kita bertambah awet dan bertambah banyak ketika kita membagikannya.
Tahun 1999 ketika saya menjadi finalis Lomba Karya Tulis Teknologi Telekomunikasi dan Informasi (LKT3I)-nya Indosat di Jakarta, saya ingat wejangan mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Beliau bilang, mengutip Al Quran, bahwa setetes tinta dari penulis itu lebih mulia dibanding darah yang tercurah dari para syuhada. Sayang, sampai saat ini saya belum memperoleh rujukan dari ayat mana dari Al Quran yang meneguhkan pernyataan menggetarkan dari beliau itu.
Mengapa memilih menulis surat pembaca ? Topiknya mutakhir. Bisa segera “diledakkan” dan bahkan segera pula melihat hasil atau dampaknya. Tahun 1973, ketika melihat sederetan pohon palem muda tak terurus, kering dan merana di Alun-Alun Utara Solo. Hal itu saya tulis di Suara Merdeka. Setelah dimuat, tanaman itu nampak disirami dan terawat. Momen ini yang menuntun diri saya menjadi seorang epistoholik, pencandu penulisan surat-surat pembaca. Sampai kini.
Seberapa sering menulis surat pembaca ? Tergantung topik dan suasana hati. Saya pernah menulis surat pembaca, sekali kirim 8 surat pembaca. Ini taktik agar ngirit, karena koran bersangkutan saat itu masih gaptek, tidak mau menerima surat pembaca via email. Untuk yang mau menerima kiriman surat pembaca via email, biasanya saya kirim 3 surat sekali kirim.
Dikirim ke mana saja ? Ketika saya tinggal dan berkuliah di UI, Jakarta, saya kirimkan ke The Jakarta Post, Kompas, Pelita, Jayakarta, Media Indonesia, Sinar Harapan, Suara Karya, beragam tabloid dan juga beragam majalah berita plus majalah hiburan.
Saat tinggal di Wonogiri sekarang ini, saya mengirimkannya ke Kompas Jawa Tengah. Kadang ke Kompas Jawa Timur. Ada koran di Jawa Tengah yang sepertinya memboikot surat-surat pembaca saya, jadi saya kini tak mengirimkan ke sana. Tak apa-apa. Toh saya kini mengelola beberapa blog dengan topik beragam. Jadi energi menulis surat pembaca ke koran itu, tetap tersalurkan melalui blog-blog saya.
Dimana kepuasannya ? Seperti kata Presiden AS ke-15, James Buchanan, yang bilang “Saya suka gaduhnya demokrasi,” maka surat pembaca saya itu berusaha ikut meramaikan karnaval kegaduhan demokrasi di Indonesia kita. Dengan cara yang elegan, melalui tulisan. Adu otak, bukan adu otot.
Menulis surat pembaca itu, bagi saya, seperti tetesan air di permukaan batu. Kalau terus saja menetes, permukaan batu itu kelak akan menjadi berlubang, tak terasa. Dalam bahasa pemasaran, menulis surat pembaca itu merupakan strategi
personal branding, menancapkan merek diri kita sendiri. Dengan frekuensi pemuatan yang bisa lebih sering dibanding pemuatan opini, aksi berderma ilmu yang dilakukan dengan cinta itu akan membuahkan sesuatu umpan balik yang tak terkirakan di masa depan.
Topik apa saja yang ditulis di surat pembaca ? Saya penulis surat pembaca kelas
omnivora, pemamah segala hal. Kebetulan saya dididik di perguruan tinggi yang khusus mengkaji seluk-beluk informasi, membuat diri saya mampu sebagai
a hound dog (bisa juga :
hound docs) yang terlatih dalam memburu dan menemukan informasi. Dengan keterampilan ini saya menjadi terbantu untuk mampu menulis surat pembaca segala topik.
Apa bedanya menulis di surat pembaca dan kolom opini ? Menulis surat pembaca adalah menulis ledakan. Harus pendek, menggigit dan pesannya segera sampai. Sementara menulis opini membutuhkan renungan yang lebih panjang, disiplin berpikir yang lebih ketat dan teratur. Lebih sering ditolak, kadang alasannya bikin jengkel dan menyiutkan nyali untuk menulis lagi. Keduanya pernah dan terus saya jalani sampai kini.
Apa cita-cita tertinggi mengenai surat pembaca ? Sebagai pendiri komunitas penulis surat pembaca, Epistoholik Indonesia, saya ingin setiap orang itu menjadi penulis surat pembaca yang merangkap sebagai blogger juga. Fenomena ini ideal dan bagus bagi demokrasi.
“Dengan mata yang cukup, kutu pun bisa ditemukan dengan mudah.” Demikian bunyi Hukum Linus, yang diambil dari nama Linus Torvald, penemu piranti lunak
open source Linux yang fenomenal. Ia sengaja membuka kode peranti lunaknya itu kepada masyarakat luas sehingga dapat segera ditemukan kutu-kutunya, yaitu cacat, kekurangan, dan kemudian upaya ramai-ramai memperbaikinya.
Bila semua warga menjadi pelaku jurnalisme warga, mekanisme
check and balances dalam kehidupan bernegara, menjadi berjalan. Asal anomali parah seperti kasus yang menimpa Prita Mulyasari dan Khoe Seng Seng dkk. itu tidak terjadi lagi, di mana mereka yang menemukan “kutu-kutu” ketidakadilan dan kecurangan justru terancam ditendang masuk penjara.
Suka baca buku ? Buku apa yang disuka ? Sebutkan judul dan penulisnya bila ingat. Ya. Saat ini saya suka buku-buku mengenai teknologi informasi (TI). Salah satu buku TI yang inspiratif adalah Being Digital (1995), karya Nicholas Negroponte. John Hagel III dan Arthur G. Armstrong, NetGain (1997), The Tipping Point (2000) karya Malcolm Gladwell, sampai Unleashing The IdeaVirus (2001) karya Seth Godin.
Sejak kapan suka baca buku ? Saat klas 4-5 SD, tahun 1963-1964, di SD Negeri Wonogiri 3, Wonogiri.
Buku-buku apa yang dibaca semasa dulu itu ? Komik semisal cerita Baratayudha dan Siti (
Wonder Woman) Gahara. Serial Nogososro-Sabuk Inten, yang paling berkesan, karena selain cerita yang menarik, dan proses pembeliannya melibatkan hubungan unik ayah dan anak.
Ayah saya bertugas di Yogya, setiap Sabtu pulang ke Wonogiri. Kalau ada buku yang ingin saya baca, saya tulis di carik kertas data bukunya, lalu diam-diam saya masukkan ke kantong baju beliau. Minggu depan, saya berharap memperoleh bacaan baru, ketika ayah saya pulang. Saya mengikat cinta dan hormat saya terhadap ayah saya (Kastanto Hendrowiharso) melalui buku dan buku.
Siapa yang mengenalkan pada membaca ? Sebelum SD, di rumah nenek saya di Kedunggudel, Sukoharjo, ada Pak Lurah mengajak saya untuk melihat papan peraga yang digunakan para tuna aksara, warga buta huruf, untuk belajar membaca.
Di rumah nenek ini ada tumpukan buku dan majalah Sosiawan (Depsos) dan Penyebar Semangat milik Pakde (Sutono) yang seorang guru. Bacaan itu yang membuat kunjungan ke rumah nenek itu sebagai kegiatan favorit. Ayah saya juga suka mendongeng, dan di rumah kebetulan ada juga koran tetapi tidak ada bacaan.
Apa makna membaca bagi Anda ? Membuka diri untuk memperoleh virus-virus wawasan baru. Untuk terus-menerus mendidik diri sendiri. Saya ingat nasehat John Howkins dalam bukunya The Creative Economy : How People Make Money From Ideas (2001), yang bilang agar kita selalu memperbarui diri sendiri.”
Leave school early, if you want, but never stop learning,” tegasnya.
Sekarang seberapa sering membaca ? Setiap hari, walau yang saya baca itu bukan melulu buku. Informasi hasil unduhan dari Internet kini semakin mendominasi asupan informasi bagi saya.
Apakah membaca membantu Anda dalam menulis ? Pasti. Menulis dan membaca itu, bagi saya, seperti aktivitas metabolisme dalam tubuh. Dengan menulis, saya seperti melakukan aksi donor darah. Darah saya disedot secukupnya, syukur-syukur kalau bisa secara teratur. Kemudian saat saya membaca, seolah saya memperoleh darah-darah yang baru untuk mengalir di tubuh saya.
Lima buku favorit ? Seperti saya sebut sebelumnya, antara lain Being Digital (1995) karya Nicholas Negroponte, John Hagel III dan Arthur G. Armstrong, NetGain (1997), The Tipping Point (2000) karya Malcolm Gladwell, sampai Unleashing The IdeaVirus (2001) karya Seth Godin, sampai The Long Tail (2006)-nya Chris Anderson.
Diantara 5 buku itu mana yang paling menjadi titik kisar dalam hidup? Ceritakan singkat. Being Digital (1995) dari Nicholas Negroponte. Bagi saya, inilah buku TI yang mampu membuat saya menitikkan air mata, sekaligus bangga untuk selalu dan berulang kali menceritakannya.
Dalam satu artikel di majalah Forbes, Negroponte yang pelopor gerakan
One Laptop For Child itu, mengatakan bahwa Internet adalah gempa bumi berkekuatan 10,5 Skala Richter yang mengguncang-guncang sendi-sendi peradaban manusia.
Buku ini mengantar saya, selain berpikir secara analog, juga membuka cakrawala yang lebih luas dan menantang dalam mencari dan menemukan solusi segala macam masalah dengan cara-cara budaya digital. Kasus Prita itu kasus digital, tetapi solusinya secara analog oleh fihak RS Omni.
Akibatnya, yang mungkin tidak mereka rasakan, tindakan mempidanakan Prita itu membuat citra dirinya (RS Omni itu) justru hancur lebur dalam ingatan abadi masyarakat yang terekam dalam kenangan digital kita bersama, yang tak bisa terhapuskan selamanya.
Buku ini membuat saya menangis karena memberi ilham dari sikap optimistis Negroponte bahwa gaya hidup digital akan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.
“
Yang mampu memberikan kebahagiaan puncak, bukanlah karena buku saya ini menjadi best-seller di mana-mana, tetapi ribuan email yang saya terima dalam tahun-tahun terakhir ini. Para orang tua mengucapkan terima kasih kepada saya ketika menjelaskan apa yang dikerjakan oleh anak-anak mereka kini dan mungkin yang akan datang. Para kaum muda mengucapkan terima kasih karena tertular antusias saya. Tetapi kepuasan nyata dan ukuran keberhasilan yang paling bermakna adalah ibu saya yang berumur 79 tahun, sekarang ini mengirimi email kepada saya setiap harinya.”
Alinea terakhir dari buku Being Digital ini yang mampu membuat saya menangis. Sekaligus bangga untuk selalu saja ingin menceritakannya.
Wonogiri, 21/8/2009
beha
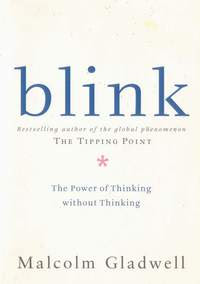 Polisi yang brutal. Polisi kulit putih dan profesor Harvard berkulit hitam hampir saja memicu berkobarnya sentimen rasial di Amerika Serikat.
Polisi yang brutal. Polisi kulit putih dan profesor Harvard berkulit hitam hampir saja memicu berkobarnya sentimen rasial di Amerika Serikat.