Oleh : Bambang Haryanto ||
 | |
| Berbeda Jalan Satu Tujuan Jilid 2. | |
Anak SD itu menendang pintu mobilnya kardinal. Lalu dia pulang dan merasa telah melakukan kuajiban sebagai seorang muslim yang baik. Karena telah mengekspresikan rasa kebenciannya terhadap penganut agama lainnya. Bahkan pimpinannya.
Anak SD itu saya sendiri. Kejadiannya pada tahun 1965 atau 1966.
Pulang dari bersekolah di SD Negeri 3 Wonogiri, saat itu duduk di klas 5 atau 6, saya menemui kerumunan di sebuah gereja kecil dekat sekolah saya. Ada keramaian.
Dalam spanduk tertulis ucapan selamat datang untuk Uskup Agung Justinus Darmojuwono. Beliau berkedudukan di Semarang. Sedang berkunjung ke Wonogiri. Beliau kemudian pada tahun 1967 menjadi kardinal yang pertama di Indonesia.
Melihat mobil yang dipakai beliau terparkir di pinggir jalan, saya menendang pintunya. Saat itu tidak ada orang lain yang memerhatikan ulah usil saya tersebut.
Dari mana perbuatan tidak terpuji saya itu berasal ?
Mengilas balik, seingat saya guru agama Islam saya di sekolah dasar , Pak Muhammad Supandi, dan guru kelas saya Pak Narwoto, tidak pernah mengajarkan untuk membenci umat agama lain. Pak Narwoto, setiap seminggu sekali datang ke rumah saya, untuk mengajari saya, adik-adik saya dan teman sebaya sekampung ,untuk menghafal surat-surat dari Al Quran.
Tentu saja kedua beliau pernah bercerita di depan kelas tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memerangi orang kafir Kurais. Bahkan saya sempat berpikiran bahwa orang kafir itu adanya hanya di jaman nabi saja.
Kebencian saya atas agama lain saat itu rupanya berasal dari hantu atau genderuwo yang ada di sekolah saya. Fenomena tentang hantu dan genderuwo di sekolah ini merujuk pendapat yang disampaikan oleh pendidik sekaligus selebritas, Bill Cosby. Doktor pendidikan dari Universita Massachusetts di Amherst (AS) dan kreator acara televisi terkenal The Bill Cosby Show pernah bilang bahwa pada tiap-tiap sekolah pasti ada hantu dan genderuwonya.
Merekalah sebagai sumber-sumber informasi misterius, entah darimana datangnya, yang mengajari anak-anak seumuran sekolah dasar untuk mengenal kata-kata jorok, porno, umpatan, dan juga kebencian terhadap pemeluk agama lain. Saya mencoba merunut untuk menemukan benih permusuhan itu.
Ah, kiranya kebencian itu berasal dari beberapa teman senior yang tinggal kelas. Mereka rupanya telah membangun rasa permusuhan berdasar perbedaan agama dengan anak sebaya yang tinggal di komplek SMP non-muslim. Tidak jauh dari sekolah saya. Sebagai rasa solidaritas seagama, saya menjadi terpengaruh dan bergabung dengan mereka.
Kampung saya tinggal, Kajen, bisa disebut terbagi dalam dua wilayah. Sebelah barat, dihuni warga muslim yang taat. Disana ada komplek SD Muhammadiyah. Ada beberapa mushola. Sedang di kampung sisi timur, yang saya tinggali, boleh disebut sebagian besar warganya adalah warga Islam KTP. Saat itu tidak ada mushola. Setiap Maghrib dan Isa saya ikut sholat berjamaah di rumah Pak Margono, pensiunan tentara, juga sebagai tukang cukur, sekaligus sebagai tetua untuk memimpin doa di kampung saya.
Walau pun merasa sebagai warga kampung yang tidak kental dengan nuansa kehidupan yang agamis, tetapi rupanya bila disentuh adanya perbedaan dengan agama lain, militansi berdasarkan agama itu rasanya mudah dibangkitkan. Sehingga mudah memicu berkobarnya rasa kebencian.
Bagaimana bila kebencian dan perbedaan itu sengaja dikobarkan sejak dini kepada anak-anak ? Saya ikut menjadi saksi hal itu. Yakni pada tahun 2006, saat saya menemani teman korespondensi saya dari Inggris untuk menyantuni warga di sekitar Klaten yang menjadi korban bencana alam gempa bumi.
Dia seorang muslimah asal Indonesia. Sudah lama tinggal di Inggris. Mendirikan badan amal untuk menyantuni anak-anak korban kerusuhan etnis yang dipicu perbedaan agama di pelbagai daerah di tanah air.
Ketika kami mampir di sebuah PAUD di daerah Yogya utara, saya terkesima. Saat itu saya menjadi saksi betapa guru dari PAUD tersebut mengajari anak asuhnya yang masih balita untuk meneriakkan yel-yel : “Islam, Yes. Kafir, No!”
Realita yang menciutkan hati untuk Indonesia kita sebagai sebuah negara yang majemuk. Bagaimana kalau ada ratusan dan ribuan lembaga pendidikan anak usia dini serupa dan melakukan hal yang sama ?
Situs tirto.id (7/2/2019) telah memaparkan hasil survei yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta terhadap 2.237 guru muslim TK hingga SMA di Indonesia. Ditunjukkan bahwa lebih dari separuh atau 56,9 persen beropini intoleran (tidak tenggang rasa) terhadap pemeluk agama selain Islam. Sebagian di antaranya setuju dengan pendirian Negara Islam.
Pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa Indonesia. Apalagi bila kita menengok sejarah yang mencatat bahwa kebangkitan faham Nazi di Jerman itu dimulai dari keluarga, yang melolohi anak-anak mereka sejak dini mengenai faham superioritas bangsa Arya dan menanamkan kebencian kepada etnis lain,
“Anak-anak belajar tersenyum dari orang tua mereka,” begitu kata Shinichi Suzuki, filsuf dan tokoh pendidikan musik untuk anak-anak dari Jepang. Tentu saja, anak-anak juga belajar membenci orang atau fihak lain dari orang tua mereka. Baik dari orang tua biologisnya, juga dari orang tua yang menjadi guru mereka dan lingkungannya. Lingkungan itu, seperti yang terjadi pada diri saya, adalah lingkungan sekolah pula.
Fenomena dari ”salah asuh” di lingkungan sekolah seperti yang saya alami, dan juga yang terjadi di PAUD Yogya tersebut, pernah menjadi pokok bahasan tokoh psikologi terkemuka, Sarlito Wirawan Sarwono. Almarhum yang guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ini pernah menjadi juri, bersama Tika Bisono dan wartawan senior harian Kompas Maria Hartiningsih, saat saya mengikuti kontes Mandom Resolution Awards 2004. Bahkan kemudian Mas Ito, panggilan akrabnya, berkenan memberikan tulisan endorsement untuk buku humor politik saya, Komedikus Erektus : Dagelan Republik Kacau Balau (2010).
Di harian Kompas (8 Oktober 2005) Sarlito mengkritisi metode pendidikan, terutama pendidikan keagamaan, yang terlalu menekankan sejak dini agar anak-anak seusia TK-SD mampu menghafal ayat-ayat suci sampai doa-doa. Bahkan ketika ujian juga seperti itu.
Dia menegaskan bahwa proses pendidikan yang ideal adalah melalui tahapan berbuat dulu (psiko-motorik), timbul pemahaman (kognitif) dan lalu timbul sikap (afektif). Saat duduk di tingkat TK-SD anak-anak diajari mengucapkan terima kasih, sudah mencium tangan ayah dan ibu atau belum, sampai sudah memberi makanan hewan kesayangannya atau belum.
Praktik budi pekerti tersebut seperti menyayangi hewan peliharaan, menghargai orang lain dan berempati disebutnya akan menghindarkan anak dari sikap arogansi dan maunya menang sendiri. Pribadinya akan tumbuh sebagai manusia yang tidak akan menghujat atau membunuh orang lain sambil kerongkongannya meneriakkan nama Tuhan.
tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, insan-insan yang ideal adalah mereka yang memiliki rasa tinggi dalam bertoleransi. Di luar pendidikan tentang kewarganegaraan di sekolah, ada salah satu praksis pendidikan yang selama ini tidak begitu dikenal untuk menumbuhkan sikap toleransi. Yaitu pendidikan senirupa untuk anak-anak.
Saya sendiri, pernah menerjuninya.
Saat berkuliah di Jurusan Mesin Fakultas Keguruan Teknik UNS Sebelas Maret saya kebetulan banyak berinteraksi dengan mahasiswa Seni Rupa Fakultas Sastra UNS Sebelas Maret. Pada tahun 1979 kami bersepakat menyelenggarakan worskshop atau bimbingan melukis bagi anak-anak dan remaja.
Tempatnya saat itu di Galeri Mandungan Muka Kraton Surakarta. Workshop ini menjadi kelanjutan dari bagian mata kegiatan Pusat Kebudayaan Jawa Tengah (PKJT) yang berpusat di Sasonomulyo, Baluwarti, Solo. Saya sebagai kepala sekolah, dibantu mahasiswa Seni Rupa. Antara lain : Anang Saroni, Mance Harman, Putut Handoko Pramono, Seno Subroto dan Sutarto. Selain di sanggar kami, juga membuka cabang layanan di komplek Polri Gendengan, untuk anak-anak keluarga Polri dan di Lanuma Adisumarmo untuk anak-anak warga komplek TNI-AU di Surakarta tersebut.
Saat itu kami berpendapat bahwa terdapat kesalahan besar dalam pendidikan seni rupa bagi anak-anak di jenjang pendidikan sekolah dasar. Metode yang lajim dipakai adalah mengkopi atau meniru (copy experience). Anak-anak itu mengerjakan duplikasi sebuah lukisan, bentuk atau model, dengan sesanggup mereka. Hasil akhir karya mereka akan hampir identik untuk semua anak yang mengerjakan tugas tersebut. Metode yang sejenis adalah metode diktat dimana guru mengontrol langkah demi langkah penyelesaian karya. Metode lainnya adalah mewarnai, dimana telah ditentukan sesuatu pola dan anak-anak hanya tinggal memberi warna.
Pelbagai metode di atas mempunyai sedikit sekali atau bahkan tidak memiliki nilai apa pun dalam pengajaran seni rupa untuk anak-anak. Metode tersebut sangat mempersempit kesempatan bagi anak untuk memilih, juga menggencet habis hak anak untuk mengekspresikan imajinasi dan emosi mereka.
Dalam metode mengkopi misalnya, itu hanya proses mekanikal dimana keberhasilan suatu karya tergantung pada kemampuan anak “menurun” karya aslinya. Semua karya seluruh anak akan hampir sama. Bermiripan satu sama lainnya. Perbedaan yang ada lebih banyak tergantung pada ketidakmampuan mengkopi dan bukan perbedaan berdasarkan ide atau ekspresi ide-ide mereka sendiri. Pemakaian metode yang gersang itu membuat setiap pribadi anak tidak terjadi sentuhan hati dengan apa yang dikerjakannya. Begitu pula kegiatan itu tidak melibatkan pikiran, perasaan atau pun sesuatu ide tentang apa yang sedang dikerjakannya.
Dalam metode diktat, dimana guru mengarahkan seluruh anak didiknya untuk mengerjakan sesuatu objek yang ditentukan sejak awal sampai pada penyelesaian secara detilnya, membuat anak tidak terlibat dalam suasana atau aktivitas penciptaaan dan aktivitas pendidikan. Anak-anak didorong untuk menumbuhsuburkan budaya membebek, mengerjakan sesuatu secara persis dari apa yang dikerjakan oleh orang lain. Bahkan dengan cara yang persis pula.
Anak-anak menjadi terampas haknya untuk mengembangkan pikiran dan aktivitas individualnya, yang mandiri, yang jika dibiasakan mereka akan mudah menyerah kepada setiap kehendak pemimpinnya. Mereka akan merasa aman apabila dirinya telah mengerjakan hal-hal yang diperintahkan kepadanya.
Dari metode tersebut secara jelas akan direfleksikan seberapa jauh dan seberapa dalam nilai-nilaipengajaran seni rupa itu akan menggores pada mereka. Metode itu akan membekas dan mencemari cipta mereka, lukisan mereka, juga sikap, kebiasaan dan cara berpikir, juga pola tingkah laku mereka. Dimana itu semua terbentuk dalam periode yang paling berkesan dari hidup mereka dan akan tetap mengakar dibawa ketika dirinya menuju dewasa serta akan menjadi patokan-patokan mereka.
***
Semua anak-anak suka melukis. Main corat-coret. Dimana saja. Bermain warna. Untuk mengekspresikan pikiran, perasaan dan kreativitas mereka. Sampai-sampai seorang pelukis termashur Pablo Picasso mengatakan bahwa, “semua anak adalah seniman. Yang menjadi problem adalah bagaimana mempertahankannya ketika mereka menjadi dewasa.” Di sekolah, dimana pengajaran seni rupa kebanyakan memakai metode yang tidak cocok, ibaratnya sekolah itu telah memberangus potensi-potensi, bakat seni, juga kreativitas mereka.
Dr. Ashfaq Ishaq dari International Child Art Foundation (ICAF) yang berkedudukan di Amerika Serikat pernah menulis di tahun 1988 bahwa di Indonesia terdapat 20 juta anak beresiko besar terkikis habis daya kreativitasnya (risk of diminishing creativity) ketika bersekolah. Yakni pada usia 8-12 tahun.
Dia sebutkan, anak-anak di kelas 4 SD mengalami apa yang disebut sebagai fourth-grade slump, karena cenderung berkompromi, tidak berani ambil risiko, takut bermain-main ide dan luntur spontanitasnya. Cara pencegahannya adalah dengan memaksimalkan usia mereka sebelum klas 4 tersebut untuk ditumbuhsuburkan daya-daya kreativitas mereka secara benar. Melalui pendidikan senirupa dengan metode yang benar.
Metode ekspresi kreatiafitas yang dianjurkan Blanche Jefferson dalam bukunya Teaching Arts to Children (1970) adalah metode pengajaran senirupa yang mencocoki untuk anak-anak. Metode ini memberikan kepada anak-anak kesempatan memilih ide mereka sendiri, juga memilih bahan yang mereka gunakan. Anak-anak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide mereka lewat bentuk atau warna yang mereka sukai. Demikian pula hak untuk menyusun bentuk atau warna-warna itu dibebaskan sekehendak mereka sendiri.
Kebebasan intelektual setiap individu anak untuk memilih, mengekspresikan dan mengorganisir tersebut merupakan pendidikan kesenirupaan yang memadai. Anak-anak itu diberikan kebebasan untuk memilih disebabkan karena lukisan mereka itu selalu berbeda antara satu dengan lainnya. Berdasar idemereka masing-masing mungkin akan menghasilkan lukisan pesawat terbang, sementara yang lain tertarik pertandingan sepakbola. Atau ada yang suka melukis pemandangan pantai, sementara temannya menggaruk-garuk warna untuk melukis abstrak.
Semua ekspresi tadi bersifat individual. Setiap anak melukis apa yang paling menarik bagi diri mereka dengan cara yang paling disukainya pula. Mungkin dari kelompok ada yang melukis satu objek yang sama, pohon. Tetapi hasil akhirnya akan berbeda. Entah beda unsur warna, beda bentuk atau fungsi keberadaannya. Ada yang melukis amat kompleks, ada juga yang sederhana saja.
Bentuk-bentuk yang mereka ciptakan amat individual, berdasar cita rasa, keinginan, kehendak masing-masing dari mereka. Kebebasan setiap anak menyempurnakan kombinasi mereka dalam bentuk atau warna pada setiap karya, akan mencirikan karya mereka sebagai ekspresi kreativitas.
Sehingga walaupun dalam situasi yang disebut belajar, setiap anak memiliki kebebasan masing-masing. Mereka bebas dari control pengajarnya. Juga bebas dari pengaruh atau paksaan dari teman-temannya. Mereka masing-masing mempunyai kesempatan untuk memilih, untuk mengekspresikan dan menyusunnya tanpa ada campur tangan fihak lain, sehingga anak-anak itu mampu menentukan kehendaknya sendiri. Mereka tidak berkuajiban terpengaruh sesuatu standar kecuali standar yang mereka pilih sendiri!
Sejak dari langkah penentuan ide dan berlanjut dalam proses penciptaan karya seni, melukis, anak-anak itu diberikan kebebasan, rasa mandiri dengan idenya dan membabarkannya seiring emosi lewat tangannya ke dalam lukisan mereka. Dinamika inilah yang disebut sebagai pengalaman kesenian. Rasa kebebasan, keserbabolehan (permissiveness), suasana yang hangat, toleran, saling menghargai satu sama lainnya, penuh suasana perasaan hati, merupakan elemen-elemen terpadu dalam pendidikan kesenirupaan.
Panorama indah dan nilai-nilai luhur dari pendidikan kesenirupaan yang bila ditanamkan dan dihayati anak-anak kita sejak dini, termasuk upaya memupuk sikap toleran dan saling menghargai satu sama lainnya antarmereka dalam perbedaan, adalah embrio interaksi antar anakbangsa yang harmoni dan pantas untuk terus ditumbuhsuburkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara-cara yang menyenangkan dan membahagiakan pada usia emas mereka.
Berikan kepada anak-anak balita Anda pensil warna dan kertas. Ajaklah mereka untuk menggoreskan sesuatu yang disukainya. Pujilah karya-karya unik mereka. Jangan hakimi karya mereka dari kacamata orang dewasa, dari kacamata Anda. Kalau memungkinkan, sediakan pojok bangunan rumah Anda sebagai sarana bermain dan mengajak anak-anak sebaya dari tetangga, untuk melukis bersama-sama.
“Hasil pendidikan yang paling tinggi adalah toleransi,” begitu tutur Helen Keller. Salah satu cara terbaik sekaligus indah untuk meraihnya bisa dimulai dari rumah Anda. Dengan berbekal kertas gambar dan crayon warna-warni untuk anak-anak tercinta Anda.
Wonogiri, 29 Mei 2021
Artikel ini dengan judul “Belajar Toleransi dengan Melukis” termuat dalam buku Berbeda Jalan Satu Tujuan : Kumpulan Kisah Tentang Toleransi – Jilid 2. Editor : RatihPoeradisastra. Jakarta : Read & Write Creative Writing, 2021.




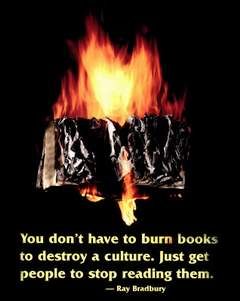


No comments:
Post a Comment