Pencetus Hari Suporter Nasional 12 Juli (2000)
Tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI)
 Kita dan Tiga Piala Dunia. “Indonesia adalah Brazilnya Asia. Pesepakbola Indonesia bermain dengan intelejensia dan bakat unik yang tidak ada duanya di dunia. Bakat-bakat mereka lebih baik dibanding pemain Korea atau Jepang. Pada era 50 dan 60-an, tim-tim Asia jangan bermimpi mampu menaklukkan tim Asia Tenggara.”
Kita dan Tiga Piala Dunia. “Indonesia adalah Brazilnya Asia. Pesepakbola Indonesia bermain dengan intelejensia dan bakat unik yang tidak ada duanya di dunia. Bakat-bakat mereka lebih baik dibanding pemain Korea atau Jepang. Pada era 50 dan 60-an, tim-tim Asia jangan bermimpi mampu menaklukkan tim Asia Tenggara.” Itulah kenangan Sekjen Asian Football Confederation (AFC), Peter Velappan, di Asiaweek (5/6/1998) menjelang Piala Dunia 1998. Tetapi di mana kini Indonesia dalam percaturan sepakbola Asia Tenggara ? Apalagi di Asia, dan tingkat dunia.
Sepakbola kita hanya mampu memiliki masa lalu dan seorang Eduardo Galeano, penulis-novelis Uruguay dalam buku bunga rampai indah tentang sepakbola, Football In Sun And Shadow (2003), mencatat nama Indonesia terkait penyelenggaraan Piala Dunia, tahun 1998, 1966 dan 1938.
Piala Dunia 1998 di Perancis dicatat Galeano berbarengan suasana dunia berkabung meninggalnya penyanyi Frank Sinatra. Dibayangi aksi mogok pekerja maskapai Air France, 32 tim tiba di stadion elegan Saint Denis untuk mengikuti piala dunia terakhir abad 20.
Perancis jadi juara dengan meremukkan tim favorit lainnya, Brasil, 3-0. Indonesia menjadi cerita latar belakang Piala Dunia 1998 bukan mengenai sepakbolanya. Tetapi tentang runtuhnya kediktatoran Soeharto yang digulung gerakan mahasiswa di bulan Mei 1998.
Indonesia disebut Eduardo Galeano lagi ketika Piala Dunia 1966 di Inggris. Peristiwa dunia terkait antara lain Che Guevara naik daun di Bolivia. The Beatles menguasai dunia. Enambelas tim ikut ambil bagian. Sepuluh tim Eropa, lima Amerika Latin, dan anehnya, Asia diwakili Korea Utara. Untuk pertama kali seluruh pertandingan disiarkan televisi, walau masih hitam-putih. Inggris meraih Piala Dunia setelah menaklukkan Jerman, 4-2. Portugal juara ketiga dan Uni Sovyet di tempat keempat.
Apa catatan tentang Indonesia ? Meletusnya peristiwa G 30 S/PKI. Terbunuhnya ratusan ribu warga Indonesia, sekaligus mengantar naiknya Soeharto sebagai penguasa Indonesia selama 32 tahun kemudian.
Piala Dunia 1938 oleh Galeano disebut sebagai kejuaraan Eropa. Hanya dua negara Amerika Latin ikut, dikeroyok sebelas negara Eropa. Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda hadir di Paris sebagai satu-satunya tim yang mewakili sisa negara di dunia lainnya.
Dalam pertandingan pertama di Reims, Indonesia ditekuk calon finalis Hungaria, 6-0. Itulah pengalaman pertama negara yang kini berpenduduk lebih dari 228 juta jiwa yang rata-rata gila sepakbola ini mencicipi terjun sebagai finalis dalam perhelatan akbar Piala Dunia.
Disekap budaya Jawa. Setelah hampir 70 tahun keterpurukan itu, mengapa sepakbola Indonesia tidak pernah mampu lagi berbicara di tingkat dunia ? Freek Colombijn, antropolog lulusan Leiden, mantan pemain Harlemsche Football Club Belanda, mengungkap analisisnya yang menarik.
Dalam artikel "View from the Periphery : Football in Indonesia" dalam buku Garry Armstrong dan Richard Giulianotti (ed.), Football Cultures and Identities (1999), ia memakai pisau bedah dari perspektif budaya dan politik untuk menggarisbawahi keterpurukan prestasi sepakbola Indonesia sebagai akibat masih meruyaknya budaya kekerasan dan belum kokohnya budaya demokrasi di negeri ini.
Ditilik dari kajian budaya, Indonesia kuat dipengaruhi budaya suku mayoritas, Jawa. Budaya Jawa memiliki pandangan ketat mengenai pentingnya keselarasan. Perasaan yang terinternalisasi secara mendalam dalam jiwa orang Jawa adalah kepekaan untuk tidak dipermalukan di muka umum.
Perasaan demikian memupuk konformitas, pengendalian tingkah laku dan menjaga ketat harmoni sosial. Konflik yang terjadi diredam sekuat tenaga. Reaksi normal setiap orang Jawa dalam menanggapi konflik adalah penghindaran, wegah rame, dan mediasi oleh fihak ketiga. Apabila meletus konflik, terutama ketika saling ejek dan saling hina terjadi, maka yang muncul adalah perasaan malu dan kehilangan muka.
Dengan landasan sikap interaksi tipikal seperti itu, membuat pertandingan sepakbola menjadi problematis. Sebab sepakbola adalah konflik eksplisit, dimana seseorang sangat mudah untuk merasa dihinakan. Adanya tackle keras, trik licin mengecoh lawan, sampai keputusan wasit yang mudah ditafsirkan secara beragam, membuat penghindaran jadi mustahil.
Apalagi ketegangan diperburuk fakta bahwa tindak penghinaan tersebut terjadi di depan ribuan pasang mata. Reaksi tipikal orang Jawa ketika dibawah tekanan semacam adalah ledakan kemarahan dan amuk tindak kekerasan.
Tesis itu dinilai parsial dan hipotetis. Karena argumen yang sama kurang meyakinkan bila diterapkan bagi kelompok etnis Indonesia lain, yang juga memunculkan tindak kekerasan serupa dalam teater sepakbola. Idealnya kemudian, penjelasan secara kultural tadi direntang dengan menggambarkan kesejajaran secara spekulatif antara sepakbola dengan budaya politik, sehingga mencakup pemain dan suporter dari semua latar belakang etnis di Indonesia.
Dalam budaya demokrasi, kalah atau menang secara fair play merupakan bagian sah suatu kompetisi atau pertandingan. Tetapi di pentas sepakbola Indonesia, kerusuhan suporter masih mudah meruyak ketika suatu tim mengalami kekalahan.
Realitas ini menegaskan betapa dalam masyarakat non-madani ide semua kompetisi selalu melibatkan konflik, belum berurat dan berakar. Bahkan tingkah laku menjunjung tinggi sportivitas dipandang sebagai hal bodoh. Teater sepakbola Indonesia kaya dengan contoh pelecehan terhadap sportivitas olahraga.
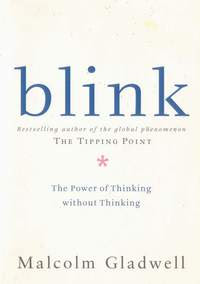
Sepakbola gajah. Salah satu yang paling melegenda adalah babak perempat-final Piala Tiger 1998 di Hanoi, Vietnam. Peristiwa hitam terjadi ketika tim yang bertanding, Thailand dan Indonesia, sama-sama tidak menggubris etika dan roh olahraga itu sendiri, yaitu sportivitas. Kedua tim justru berusaha mati-matian agar mereka memperoleh kekalahan pada akhir pertandingan. Tujuannya, agar terhindar bertemu tuan rumah Vietnam di semi-final.
Saat skor 2-2 pada masa perpanjangan waktu, pemain Indonesia Mursyid Effendi sukses besar, menembak ke arah gawang timnya sendiri. Kiper Indonesia saat itu juga tidak berusaha menepis. Tetapi justru banyak pemain Thailand yang berusaha menjaga gawang timnas Indonesia agar tidak kebobolan.
Aib paling mutakhir yang mencoreng wajah persepakbolaan nasional adalah terkuaknya kasus suap klub Penajam Medan Jaya kepada petinggi PSSI, yang jelas semakin menunjukkan betapa semangat berkompetisi secara fair play masih impian langka di Indonesia.
Atau dalam pandangan psikolog Jo Rumeser (Kompas, 9/6/2007), kasus hitam itu terjadi karena dalam tubuh PSSI diisi orang-orang yang tidak tahu esensi olahraga sehingga memungkinkan munculnya kasus-kasus pengingkaran sportivitas seperti suap dan kolusi pengaturan skor.
Di tengah ancaman meruyaknya tindak kekerasan suporter kita dan lilitan budaya korupsi dalam tubuh organisasinya, bulan Juli 2007 ini timnas Indonesia terjun dalam Piala Asia 2007. Kita dapat bercermin tentang prestasi tim kita di kancah Asia, walau dua tahun lalu saya pernah menemukan cermin buram wajah sepakbola Indonesia dari buku keduanya Malcolm Gladwell, Blink : The Power of Thinking without Thinking (2005).
Buku itu saya beli usai mendukung timnas di leg 2 Final Piala Tiger 2004 di Singapura. Gladwell punya tesis, untuk menilai sesuatu keadaan secara akurat kita dapat melakukannya hanya dengan sekejap mata, dengan mengambil thin slice, irisan kecilnya.
Rasa ingin tahu saya, “Mengapa Singapura mampu menjadi juara Piala Tiger 2004, berprestasi tinggi dan Indonesia harus keok dan terpuruk lagi ?” Dalam penerbangan pulang, dengan mengambil tesisnya Gladwell saya memberikan jawaban :
Ho Peng Kee, presiden FAS/Football Association of Singapore adalah seorang profesor. Nurdin Halid, Ketua PSSI kita, seorang koruptor.
[Artikel ini dengan judul “Sepakbola : Cermin Korup dan Ambivalensi Kita” pernah dimuat di kolom Teroka-Humaniora, Harian Kompas, Sabtu, 8 September 2007. Dalam pemuatannya telah dilakukan penyuntingan].
Data buku rujukan :
Eduardo Galeano, Football in Sun and Shadow. London : Fourth Estate, 2003. 241 halaman. Buku ini hadiah tak terduga dari Andibachtiar Yusuf, sineas, 29 Maret 2006.
Freek Colombijn, “View from the Periphery : Football in Indonesia” dalam Gary Armstrong dan Richard Giulianotti (ed.), Football Cultures and Identities. London : Macmillan Press, 1999. 251 halaman. Artikel ini saya fotokopi 21 Maret 2002 di Perpustakaan British Council, Jakarta. Satu bulan kemudian saya memenangkan Honda The Power of Dreams Contest 2002, mengusung impian merubah budaya suporter sepakbola yang destruktif menjadi kelompok penampil dalam konser suporter sepakbola yang kolosal dan atraktif.
Malcolm Gladwell, Blink : The Power of Thinking without Thinking. London : Penguin, 2005.277 halaman. Buku ini dipajang secara masif di papan peraga toko buku Borders, Orchard Road, Singapura, 18/1/2005. Saya sudah ngebet berat, tetapi “nanti dulu, ah.” Sasaran utama saya saat itu adalah mencari buku mengenai KM, manajemen ilmu pengetahuan.
Di Borders, tak ada. Di Kinokuniya, masih di Orchard Road juga, ada rak untuk topik KM. Tetapi buku terbitan Harvard yang saya cari, tak ada. Ketika mau boarding, buku Blink ini kembali melambai saya lagi di toko buku TimesNewsLink di Changi itu.
Saya sempat tergoda buku kumpulan lelucon mengenai David Beckham [“Anda tahu ciri-ciri komputer yang baru saja dipakai oleh Beckham ? Di monitor banyak bekas Tipp-Exnya”], akhirnya buku Blink ini terbeli juga. Juga majalah Fortune Vol. 151, No. 1, 24 Januari 2005 yang memajang laporan utama “10 Tech Trends To Watch in 2005,” di mana tren nomor satunya mengenai blog dan blogger.
kbk




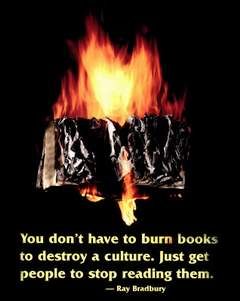


No comments:
Post a Comment