Email : humorliner (at) yahoo.com
 “Pertandingan tenis bintang lima !”
“Pertandingan tenis bintang lima !”Demikian ungkapan plastis komentator tenis Star Sports, Vijay Amritaj, sore kemarin (24/1). Ia mengomentari babak akhir pertandingan menegangkan antarsesama petenis Belgia, Justine Henin melawan yuniornya Yanina Wickmeyer.
Saya pun ikut tegang saat Henin ketinggalan angka.
Tetapi menurut Vijay, bekal “pengetahuan dan pengalaman” dari pemegang 7 gelar juara Grand Slam dan atlet kebanggaan negeri kecil yang merdeka tahun 1830 (di Indonesia saat itu meletus Perang Diponegoro) yang membuatnya lolos dari lubang jarum.
Vijay juga mengatakan bahwa pertandingan itu telah mencuatkan sinyal bahaya bagi petenis putri dunia lainnya.
Bunyi sinyal itu demikian tegas : di masa mendatang, waspadailah Yanina Wickmeyer !
Juga, Fernando Gonzalez. Itu bisik saya.
Tentu saja untuk kalangan petenis pria. Pendapat saya ini merupakan wujud sebagai makmum atas prediksi Vijay ketika petenis Chile itu, unggulan 11, menjelang bertarung melawan petenis unggulan 7 asal AS, Andy Roddick.
Malam itu hampir saja mengirim SMS ke sobat saya, seorang tennis buff asal Solo, Pedhet Wijaya. Tokoh inovatif yang malang melintang di bisnis radio Bandung dan Solo ini, juga pernah mengentak dunia dengan menyelenggarakan festival keroncong internasional di Solo, Desember 2008, saat ini sedang menonton langsung hajat tenis akbar di Melbourne tersebut. Saya ingin tahu, Pedhet Wijaya ini menjagoi siapa : Roddick atau Gonzalez ?
Kurva presisi. Bagi saya, petenis kelahiran Santiago 27 tahun lalu itu, anggun bermain seperti ular. Kalau Roddick tampil meledak-ledak dengan gedoran servis as, bertubi-tubi, Gonzalez menggelesar kanan-kiri, dengan pengembalian bola yang sepertinya tidak bertenaga.
Tetapi ketika Roddick berada pada posisi bolong, ular Chile itu segera mematuk dengan bisanya. Meneroboskan bola secara halus pada ruang yang sempit. Mengiris ruang sehingga bola jatuh down the line dengan presisi tinggi. Atau secara cerdik melambungkan bola sebagai garis dengan kurva terukur sehingga jatuh di balik punggung petenis asal negeri Paman Sam itu.
“Dazzling and glorious shoot !”
Demikian seru Vijay Amritaj memuji.
Berkali-kali.
Tetapi tarian ular asal negeri yang pernah diperintah kubu Marxis Demokrat dengan presidennya Salvador Allende, tidak berlanjut paripurna. Sekadar info, nama Allende dipakai sebagai nama salah satu anak pejuang HAM kita, almarhum Munir yang kasusnya pembunuhannya digantung pemerintahan SBY sampai saat ini. Salvador Allende pada tahun 1973 dijatuhkan oleh junta militer yang represif pimpinan jenderal Augusto Pinochet.
Kembali ke Fernando Gonzalez. Diterpa beruntun kesalahan sendiri di saat kritis, terlibat berbantahan dengan wasit, menendang botol minum, sampai membanting raketnya hingga penyok, menandakan ia dibelit rasa frustrasi berat. Pertandingan, dengan meminjam judul lagunya John Lennon sebagai mind game itu, menjadi semakin berat bagi Fernando.
Karena dirinya pertama-tama harus bertarung melawan diri sendiri dulu. Konsentrasinya buyar. Akhirnya ia harus mengakui kemenangan Andy Roddick, 3-2.
Selamat tinggal, Fernando !
Semoga lain kali kita ketemu lagi, sehingga saya bisa menyanyikan lagunya ABBA yang terkenal ini untukmu :
Can you hear the drums Fernando?
I remember long ago another starry night like this
There was something in the air that night
The stars were bright, Fernando
They were shining there for you and me
For liberty, Fernando
Menantang resiko. Saya memilih Fernando Gonzalez karena saya cenderung suka menjagoi para underdog. Justine Henin juga underdog dalam turnamen Australia Terbuka 2010 ini. Ia bisa ikut dengan fasilitas wild card, bukan ?
Pilihan semacam itu tentu mengundang resiko yang lebih besar. Kebetulan isu terkait resiko ini, dengan judul “Dipimpin Oleh Resiko,” pada malam yang sama menjadi topik acara Golden Ways-nya Mario Teguh di MetroTV.
Inti pesannya adalah, kalau Anda takut terhadap resiko atau menghindari resiko, Anda tidak akan pergi kemana-mana.
Pesan serupa juga muncul sebelumnya dalam artikel Rhenald Kasali di Kompas, terkait usrek pengusutan kasus Bank Century. Menurutnya, bangsa Indonesia kini cenderung bersikap fundamentalis (istilah dari saya), yang harus selalu benar seperti malaikat. Salah sedikit saja, dirinya harus memperoleh hukuman setimpal. Malah berlapis-lapis.
Pendekatan seperti ini, menurut saya, akan hanya menghasilkan kelompok insan-insan medioker, under taker dan juga care taker. Mereka itu bukan sebagai inventor atau inovator yang senantiasa berperangai sebagai risk taker.
Sayangnya, kualitas yang pertama itulah yang selama ini terjadi pada pendidikan kita.
Lembaga pendidikan kita senantiasa jauh lebih banyak melahirkan para bebek, yang suka status quo dan membebek, daripada melahirkan insan-insan yang mampu berpikir merdeka yang metaforanya selalu muncul dalam bagian akhir tulisan ilmuwan politik asal UGM, Riswandha Imawan almarhum : eagle flies alone.
Indonesia kita memiliki lambang garuda, tetapi justru bangsa ini sekarang banyak sekali melahirkan bebek-bebek yang suaranya riuh dan mengerubunginya. Lihat saja pemandangan dalam gedung DPR. Termasuk dalam rapat-rapat pansus kasus Bank Century. Utamanya kuak-kuak suara seekor bebek robot yang mengumpat sana-sini, ia semata berteriak untuk mengacaukan paparan lawan politiknya.
Jutaan calon bebek lainnya, kini sedang mengeram di kandang-kandang yang bernama lembaga pendidikan kita. Mereka tiap hari dilolohi doktrin, yang menurut konsultan kreativitas dari Lembah Silikon Roger von Oech dalam bukunya A Whack On The Side Of The Head : How To Unlock Your Mind For Innovation (1983), senantiasa berusaha mencari “satu jawaban yang benar.”
Pendekatan tunggal di atas boleh jadi tepat untuk situasi tertentu. Tetapi bahayanya, kebanyakan bertendensi menghentikan upaya untuk memperoleh jawaban alternatif benar lainnya, setelah jawaban pertama itu diperoleh.
Pendekatan seperti ini patut disayangkan. Karena seringkali jawaban benar yang kedua, ketiga atau yang kesepuluh, merupakan jawaban yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah secara inovatif.
Terima kasih, Roger.
Buku merah itu saya beli tanggal 2 April 1997. Pas ada obralan di Toko Buku Gramedia Matraman, Jakarta. Untuk sekadar tanda, saya tulis pada salah satu halaman depannya : “..buku ini sudah aku impikan untuk aku miliki, sekitar 5-10 tahun yang lalu…dibeli dari honor artikelku, Ambisi Microsoft di tahun 1997, di Media Indonesia, 23 Januari 1997.”
Konsultan kreatif untuk Apple, ARCO, Colgate-Palmolive, IBM, NASA sampai Xerox ini, dalam mengenalkan diri antara lain menulis, “Saya menulis disertasi tentang filsuf Jerman Abad 20, Ernst Cassirer, manusia serba bisa yang terakhir. Darinya, saya belajar bahwa menjadi seorang generalis merupakan hal yang baik, dengan melihat Gambar Besar mendorong kita mampu bersikap fleksibel.”
Sebagaimana penilaian komentator tenis favorit saya Vijay Amritaj yang penderita asma itu terhadap pertandingan Henin-Wickmeyer di Australia Terbuka 2010 di minggu malam itu, saya makmum sekali lagi dalam memberi komentar untuk pendapat Roger von Oech di atas :
“Itu pendapat bintang lima !”
Apa pendapat Anda ?
Wonogiri, 25 Januari 2010




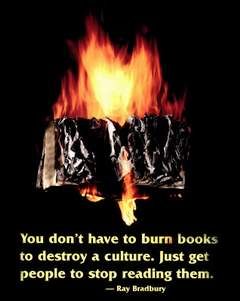


Kalo sudah dibaca bukunya bisa saya beli pak?
ReplyDelete